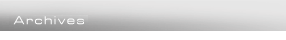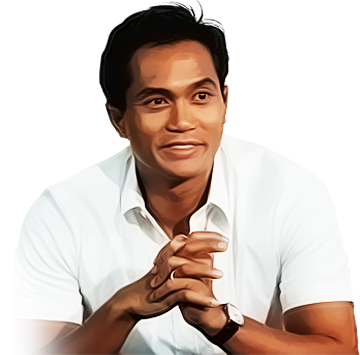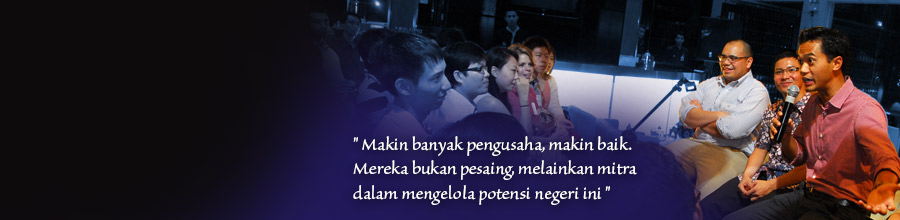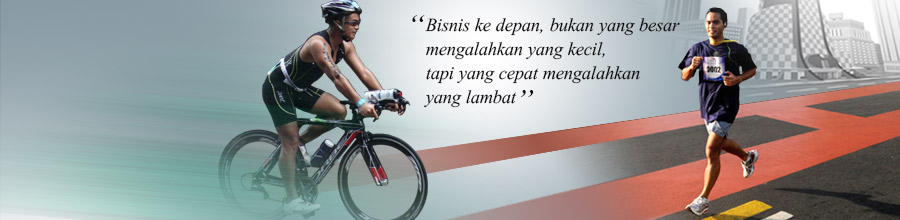-
posted by Anindya Feb 11th, 2012
 “Corporate shared value” can be a new capitalist model for companies to make money as well as to cope with social needs”.
“Corporate shared value” can be a new capitalist model for companies to make money as well as to cope with social needs”.Kalimat di atas adalah salah satu dari wawasan baru yang saya dapatkan dari Profesor Michael E. Porter, guru besar manajemen bisnis dan competitiveness dari Universitas Harvard. Saya mengikuti sesi Michael Porter yang dikemas dalam diskusi mengenai masa depan perusahaan modern, dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) yang digelar di Davos, Swiss, 25-29 Januari 2012.
Ini kali kedua saya mengikuti ‘kelas’ Porter. Pertamakali berjumpa dia di Boston, saat acara diskusi terbatas bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tahun 2009.
Pada intinya Michael Porter membagikan wawasan mengenai perlunya menerapkan konsep Corporate Shared Values (CSV) ketimbang Corporate Social Responsibility (CSR) yang selama ini banyak diterapkan oleh perusahaan, termasuk perusahaan di grup kami. Konsep CSV menarik dan lebih berkelanjutan karena intinya adalah growing together with society, ketimbang sekedar do no harm to society.
Konsep CSV menempatkan masyarakat termasuk pemangku kepentingan ( dan pemasok) sebagai mitra, sesama subyek. Sementara konsep CSR cenderung menempatkan pemangku kepentingan sebagai obyek. Semacam redistribusi kekayaan. Dalam padangan Porter, CSR cenderung menjadi aktivitas yang terpisah dari “bisnis inti/core business”. Adalah ‘responsibility’ perusahaan untuk menjadi “ a good corporate citizen”, padahal perusahaan memiliki keterbatasan kemampuan dalam membagi laba usaha ataupun meredistribusikan kekayaan, juga memberikan donasi.
Menurut saya, konsep CSV yang disampaikan Porter di WEF Davos menjadi terobosan dan cara pandang baru dalam mempraktikkan kapitalisme. Porter memberikan contoh sebuah perusahaan makanan membangun produk dan bisnisnya secara sukses, namun berakibat konsumen makan terlalu banyak. Kurang sehat. “Bagaimana jika ada perusahaan makanan yang membangun produk yang berkualitas tinggi dan kaya nutrisi? Di sini kita mengubah pola berpikir dan berbisnis, ” kata Porter.
Dalam praktiknya, perusahaan yang kedua membagi pola pikirnya dengan pemasok. Memastikan pemasok perusahaan makanan itu menyediakan produk yang berkualitas tinggi, termasuk makanan organik misalnya. Berapa harga yang ditetapkan sebagai harga beli dari pemasok disepakati dengan semangat kualitas terjaga dan pemasok mendapat laba yang wajar. Harga beli itu lantas dijadikan patokan harga jual perusahaan makanan yang memperhatikan aspek nutrisi bagi konsumennya. Nampak bahwa dalam jaringan pemasok-perusahaan-konsumen terjadi peningkatan kualitas yang tidak hanya berupa laba melainkan juga kesehatan.
Contoh lain yang disampaikan Porter adalah sebuah perusahaan farmasi yang sebelumnya hanya memproduksi obat-obatan untuk 400-500 juta orang yang hidup di negara maju dan berkembang yang sanggup membayar harga obatnya. “Kini mereka mengubah cara bisnis dengan memproduksi obat bagi populasi dunia yang jumlahnya 8 miliar. Mereka mengubah produksi dan saluran pasokan (supply chain), untuk memastikan semua orang bisa menjangkau produknya,” kata Porter.
Konsep CSV kini mulai dikembangkan banyak perusahaan besar. Menurut Porter, ada tiga elemen dalam konsep ini, yakni produk dengan dimensi sosial, jaringan distribusi dan pemasok, serta ekosistem kluster bisnis. Ia memberi contoh Nestle, produsen makanan dan minuman yang memilih mendapatkan pasokan kopi dari petani kecil. Di masa lalu mereka cenderung membeli produk petani dengan harga sangat rendah. Sekarang proses yang dilakukan Nestle berubah, membangun ‘engagement’, keterlibatan dengan proses produksi yang dilakukan petani pemasok, bahkan menawarkan dukungan know-how dan teknologi agar petani bisa memproduksi kopinya dengan efisien dan hasil panen yang lebih banyak dan berkualitas.
Pada intinya Michael Porter ingin mengatakan bahwa CSR tidak sustainable, atau berkelanjutan. CSV adalah bagaimana bisa bertindak sebagai kapitalis di masa kini. “It’s not a charity but something for better capitalist,” kata Porter. Dia mengajak orang tidak membenci istilah “capitalism” karena itu adalah cara untuk membangun bisnis menjadi ‘scalable’ dan bisa menghidupi dirinya sendiri dan karyawannya. Tanpa pola pikir menjadi kapitalis, orang tak akan mampu membangun bisnis menjadi besar dan bertahan lama.
Menurut saya konsep CSV yang ditawarkan Michael Porter ada plus-minusnya jika hendak diterapkan perusahaan di Indonesia. Tetapi konsep ini menarik untuk memperkaya diskusi dalam perumusan Undang-Undang Corporate Social Responsibility.
Sesi yang menghadirkan Michael E.Porter adalah salah satu dari ratusan sesi yang digelar selama berlangsungnya WEF pekan lalu. Menurut buku program ada 280 sesi yang temanya beragam, mulai dari perkembangan krisis Eropa dan Euro, manajemen dan kepemimpinan, perkembangan regional seperti di Cina, Asia, Amerika, Afrika dan Timur Tengah, sampai sesi spesial yang dilakukan di Congress Hall, ruang utama di Congress Center, lokasi berlangsungnya pertemuan WEF yang selalu diadakan tiap Januari di Davos.
Bisa dikatakan, WEF Annual Meeting ini adalah kegiatan utama di Davos-Klosters, desa indah yang berada di Pegunungan Alpen, lokasi tertinggi Eropa dan menjadi tempat tetirah orang-orang kaya dunia. Biaya hidup di sana sangat mahal, dengan fasilitas hotel yang relatif lebih sederhana ketimbang hotel berbintang di negeri kita. Harga sewa kian meroket selama berlangsungnya WEF.
Tahun ini pertemuan tahunan diikuti sekitar 2600 peserta, termasuk 50-an kepala pemerintahan, ratusan menteri kabinet dari berbagai negara, pakar, seniman, 1000an pemilik dan top eksekutif perusahaan besar di dunia, dan pemimpin lembaga multilateral seperti Sekjen PBB Ban Kin-Moon, Direktur IMF Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia Rober Zoelick. Di luar WEF Annual Meeting, WEF yang didirikan oleh Prof Klaus Schwab sejak 1971 ini telah mengembangkan diri dengan menggelar sejumlah WEF regional, termasuk di Asia.
Tahun lalu WEF Asia digelar di Jakarta. Juni tahun ini WEF Asia akan mengambil tempat di Bangkok, Thailand. Setidaknya ada tiga kegiatan regional tahunan. Kita bisa memonitornya melalui website WEF di www.weforum.org. Tentu saja yang paling spektakuler adalah WEF Davos. Saljunya juga spektakuler, tahun ini salju turun paling banyak. CNN mengatakan yang terbanyak sejak 1968! Pemandangannya sih luar biasa, indah!
Bagaimana mengorganisasikan acara sebesar itu dengan ratusan sesi dan mengundang pembicara kelas dunia, menurut saya suatu hal yang luar biasa. Salut untuk Prof Klaus Schwab. Dari tahun ke tahun minat orang mengikuti WEF kian tinggi. Peserta merasakan dampaknya yang nyata. Forum ini efektif untuk arena berjejaring, mendapat kenalan baru yang berpotensi mendatangkan bisnis, juga sarana belajar yang luar biasa. Bagi wakil negara atau pengusaha seperti saya yang juga peduli akan imej Indonesia, saya menggunakan forum ini nuntuk promosi soal negara kita juga. Setahu saya, membujuk WEF untuk menggelar acaranya di sebuah negara membutuhkan lobi khusus. WEF dianggap sebagai sebuah kelompok tertutup, yang hanya mengikutsertakan para pengusaha dan pembuat kebijakan ekonomi-bisnis. Bahkan disindir sebagai pertemuan kaum kapitalis.
Sebenarnya sejak 2008, WEF menggelar banyak sesi yang menghadirkan pembicara dan peserta dari kalangan masyarakat sipil termasuk kaum buruh. Tahun ini ada satu wakil masyarakat sipil Indonesia yang diundang jadi peserta yakni Rekson Silaban, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. WEF juga memberikan perhatian pada kesetaraan gender dengan menggelar laporan tahunan mengenai Gender Gap. Tahun ini saya baca di media, WEF Davos mencetak rekor peserta perempuan terbanyak, 17% dari total peserta. Di berbagai ruangan dan lorong Congress Center saya memang melihat banyak sekali tokoh-tokoh dan eksektif perempuan dari perusahaan top dunia seliweran. Sempat bertukar-kartu nama dengan beberapa diantaranya.
Dari Indonesia tahun ini WEF Davos dihadiri oleh dua menteri, yakni Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ibu Mari Elka Pangestu, veteran di WEF karena sudah terlibat sejak tahun 1997, serta Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Keduanya berbicara di beberapa sesi. Indonesia mendapatkan apresiasi baik secara ekonomi maupun politik di WEF. Apalagi pas waktunya baru saja mendapatkan investment grade dari dua lembaga rating, yakni Fitch dan Moody. Dari kalangan dunia usaha, ada sejumlah pengusaha seperti Pak James Ryadi dari Lippo Group, Pak Franky Oesman Widjaya dari Sinar Mas Group, para dirut BUMN seperti dirut Bank Mandiri Pak Zulkifli Zaini, Dirut Bank BNI Pak Gatot Soewondo dan Dirut Garuda Pak Emirsyah Sattar.
Sesi spesial yang diselenggarakan di Congress Hall yang bisa menampung 500-an tempat duduk, menghadirkan pemimpin dunia seperti Kanselir Jerman Angela Merkel, PM Inggris David Cameron, Presiden Zuma dari Afrika Selatan sampai panel diskusi yang mendatangkan nama besar dan langganan pembicara di WEF seperti Bill Gates. Tahun ini Mick Jagger dan Michele Yeoh, keduanya selebriti ada dalam daftar peserta. Tapi saya tidak sempat mengikuti sesi mereka, dan tidak tahu persis apakah sesi mereka jadi dilakukan. Mestinya menarik melihat bagaimana mereka mendiskusikan peran seniman di tengah kepungan diskusi soal kapitalisme, demokrasi dan globalisasi.
WEF Davos diselenggarakan bersamaan dengan situasi mendesak, Krisis Eropa. Tema besar WEF Annual Meeting 2012 adalah Great Transformation: Re-Shaping New Models. Menurut Prof Klaus Schwab, tema besar WEF tahun ini merefleksikan perlunya perubahan cara pikir, cara pandang dan cara bertindak dalam merespon situasi ekonomi global. “Kapitalisme dalam bentuknya selama ini tak lagi cocok untuk dunia kita. Kita telah gagal belajar dari pelajaran pahit krisis keuangan dunia pada 2009. Transformasi global mendesak dilakukan dan harus dimulai dengan merumuskan kembali kesadaran akan tanggung jawab sosial secara global,” kata Klaus Schwab sebagaimana dikutip di laman www.weforum.org.
Tema WEF mewarnai semangat sesi yang digelar di sana, terutama sesi terkait dengan Eropa. Misalnya, ada sesi yang judulnya “Rebuilding Europa”. Sesi lain berjudul “Re-Thinking Eurozone”. Di Eropa (dan juga AS) memang ekonomi sedang sulit, dan dunia merasakan dampaknya. Para peserta WEF dari seluruh dunia datang ke Davos untuk mendengar langsung pemimpin Eropa mengenai rencana aksi mereka menangani krisis keuangan, termasuk mata uang Euro-nya.
Salah satu sesi yang saya hadiri terkait dengan masa depan Eropa adalah “The Future of Eurozone” yang digelar di Congress Hall, 27 Januari. Ruangan penuh sesak. Pertanyaan besar yang dibahas dalam sesi ini adalah: Bagaimana ekonomi di Eurozone bangkit dari krisis? Poin diskusi mencakup mengenai restrukturisasi utang Yunani, ketidaksepakatan diantara negara anggota Uni Eropa mengenai solusi penanganan krisis, membahas prosposal terkait fiskal, meredam kepanikan di pasar uang atas krisis Euro dan berbagai sudut pandang lain.
Diskusi ini menghadirkan Olli Rehn, Vice President Economic and Monetary Affairs European Comission, Menteri Keuangan Spanyol Luis de Guindos Jurado, Menteri Keuangan Federal Jerman, Wolfgang Schauble dan Menteri Keuangan dan Industri Francois Baroin. Para menteri sepakat perlunya konvergensi dalam pengelolaan fiskal di negara anggota EU sebagai langkah penting untuk mengurangi tekanan ekonomi. Mereka juga menyatakan tekad tidak mengulangi kesalahan masa lalu untuk menghindari berulangnya krisis. “Elemen penting untuk membangkitkan kembali kepercayaan adalah penguatan kelembagaan dan komitmen semua anggota,” kata Luis de Guindos Jurado.
Kendati demikian, para menteri juga mengakui adanya perbedaan pendapat mengenai proposal mengatasi krisis utang. Misalnya isu soal Eurobonds, kesulitannya adalah Eropa harus membentuk struktur penyatuan fiskal.Yang selama ini sudah beroperasi adalah penyatuan mata uang dan pengelolaan moneter. Diskusi ini dimoderatori oleh Maria Bartiromo, anchor CNBC.
Mengikuti sesi mengenai masa depan zona Eropa ini membuat saya mengingat kembali krisis keuangan yang dialami Indonesia tahun 1997-1998. Problemnya fundamentalnya adalah utang besar karena defisit anggaran yang berlebihan dalam satu dekade terakhir dan kurang kompetitifnya produk/servis Eropa di mata dunia. Tantangannya adalah kedua hal ini sangat struktural, jadi tidak bisa diselesaikan jangka pendek. Apalagi kalau ‘market confidence’, yang merupakan pisau bermata dua, sudah mulai tererosi. Soal ini yang banyak dibahas termasuk oleh pemimpin Bank Dunia dan bahkan PM Inggris David Cameron. Kalau tidak ada solusi segera, maka Euro akan terus terpuruk.
Masalahnya, komposisi demografi Eropa, dimana penduduk nya sudah tua (dan pemakai jaringan pengaman sosial) juga sulit untuk mengimplementasi program disruptif/agresif, walau baik untuk jangka menengah dan panjangnya. Kepemimpinan di Eropa juga sulit satu suara karena masing masing mempunyai skala masalah dan konstituen berbeda. Intinya, Eurozone masih mencoba ‘gali lobang tutup lobang’ atau hidup seperti orang yang sekarat di rumah sakit, harus ditopang ’life support system’. Sampai kapan? Ini yang menjadi perhatian dunia, termasuk kita di Indonesia.
Di WEF Davos, dalam waktu bersamaan bisa digelar secara paralel 5-7 sesi diskusi. Tak bisa kita hadiri semua, tentunya. Kemasannya bisa bentuk satu tamu spesial berbicara lalu melayani tanya-jawab seperti yang dilakukan PM David Cameron, bentuk diskusi panel, wawancara one-on-one yang dilakukan oleh Prof Muhammad Yunus pendiri Grameen Bank, atau bentuk talkshow yang direkam untuk ditayangkan televisi. Salah satu bentuk talkshow televisi yang saya hadiri adalah “AP Debate On Democracy”, yang diadakan oleh kantor berita The Associated Press.
Debatnya sangat menarik, menghadirkan pemimpin partai politik Islam hasil pemilihan umum pasca revolusi di Tunisia, Menteri Luar Negeri Brasil, Menteri Luar Negeri Pakistan, Anggota Kongres dari Partai Republik, AS dan Drektur Human Right Watch. Diskusi dipandu oleh Michael Oreskes, AP senior managing editor untuk AS. Debat ini memang memiliki nuansa kuat atas Revolusi “Arab Spring” yang terjadi tahun lalu dan dimulai di Tunisia. Seperti kita ketahui, revolusi telah menjatuhkan setidaknya dua pemerintahan, yakni di Tunisia dan Mesir. Prosesnya masih terus berlangsung di sejumlah negara. Tak heran jika pertanyaan besar yang muncul sebagai dasar tema debat: is democracy up to the challenge of the 21’s century?
Debat mengeksplorasi kegagalan dalam pemerintahan yang demokratis dalam memenuhi aspirasi masyarakat, membahas bagaimana politik Islam berfungsi dalam sistem yang demokratik (Indonesia mendapat pujian dari pembicara sebagai contoh sukses), tekanan dari sistem demokrasi yang kini berkembang termasuk berbagai protes melalui demo dan media baru, institusi demokrasi yang labil serta lemahnya tradisi penghormatan terhadap hak asasi manusia di negara yang tengah membangun demokrasi. Salah satu kesimpulannya, bahkan pemerintah yang mengaku mengelola secara demokratif, seringkali gagal mengambil inisiatif menajalankan demokrasi, sehngga harus diambilalih oleh kekuatan rakyat. Ini yang terjadi dengan Arab Spring.
Pada intinya panelis sepakat demokrasi masih relevan, asal dibarengi dengan kian matangnya masyarakat dalam menjalankan demokrasi. Rachid Ghannouchi, pendiri Partai Ennahda, partai Islam yang memenangkan pemilu bebas yang pertama di Tunisia mengatakan, “Demokrasi tanpa keadilan sosial dapat terjerumus menjadi mafia.” Jadi, pemilu bebas itu sendiri tak cukup memastikan demokrasi berjalan baik. Bagaimana proses berikutnya juga penting, termasuk memastikan setiap orang punya kebebasan berekspresi. Baik Ghannouchi dan Menlu Pakistan Hina Rabbani Khar (yang masih berusia muda dan cerdas), sepakat bahwa Islam pada dasarnya memiliki nilai dasar yang mendukung sistem demokrasi. “Menurut saya, Islam selama ini menjadi agama yang paling sering disalahpahami didunia…Saya pikir Islam justru memiliki nilai demokrasi paling kental dalam pengelolaan sebuah negara ketimbang yang lainnya,” ujar Menlu Rabbani Khar.
Di luar ratusan sesi di Congress Center dan sejumlah hotel di sekitarnya setiap malam digelar beragam bentuk pesta koktail oleh wakil negara maupun perusahaan besar. Kemasan acara dan pembicaranya pun menarik. Negara seperti India, Cina, Kanada, Thailand misalnya memanfaatkan ajang WEF Davos untuk mempromisikan negara secara serius. Mereka menyewa tenpat secara khusus, mengadakan kegiatan selama berlangsungnya Davos, memasang baliho di seputar jalan yang dilalui ribuan peserta. Biayanya pasti mahal. Tapi ini forum yang bergengsi dan hampir semua investor besar hadir. Boleh jadi mereka menganggap biaya sebagai investasi.
Indonesia juga mengadakan “Co-Co Night” (Collaborations and Cooperations)yang berlangsung di See Hof Hotel, pada 26 Januari malam, dan dihadiri 300an hadirin, termasuk wakil diplomatik kita di Swiss. Malam itu pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjadi penyelenggara, didukung oleh sejumlah perusahaan termasuk Bumi Resources yang saya wakili, menyajikan hidangan kuliner Nusantara, termasuk Nasi Goreng Kampoeng dan Rendang Padang. Ke depan, saya merasa keberadaan pemerintah dan pengusaha Indonesia di WEF harus dioptimalkan melalui kerjasama, perencanaan dan koordinasi yang lebih baik sebelum berpartipasi di WEF, termasuk menggelar acara.
Menurut saya, pertemuan tahunan WEF yang digelar setiap Januari ini pas betul bagi kalangan pebisnis seperti saya (juga pemerintah dan pengambil kebijakan lainnya) untuk mengetahui apa yang bakal terjadi selama setahun ke depan. Pulang dari Davos dengan segudang wawasan, dan tambhan puluhan kartu nama dari kenalan baru, tentu membuat semangat untuk bekerja makin bergairah. Setidaknya kita bisa berharap, mereka yang hadir di Davos mendapar banyak informasi dan wawasan untuk kian cermat dan cepat membuat keputusan. Terutama untuk akhiri krisis di Eropa.
Leave a Reply
INSTAGRAM
TWITTER
FACEBOOK
-